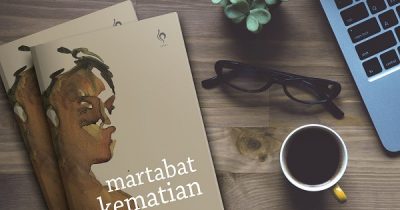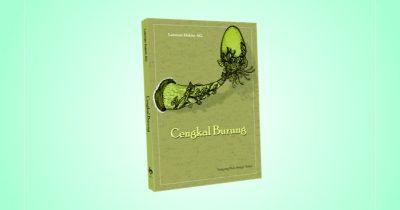Kultur Perayaan Kematian

(Resensi atas buku Martabat Kematian karya Muna Masyari)
DUNIA GAIB seperti kematian menjadi parameter bagi kita untuk mengukur antara logika dan keyakinan. Hal ini menuntut kita untuk menganggapnya ada sebagaiamana dituliskan oleh Muna Masyari dalam kumpulan cerpen ini. Pandangan masyarakat lokal di seluruh nusantara memiliki perspektif yang beragam dalam memandang hal-hal gaib. Termasuk cara Muna dalam memetaforkan kematian sebagai jalan penuh khidmat, meskipun secara logis Muna tak menelaah lebih dalam tentang hakikat kematian, kecuali hanya demi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Tapi, memang benar apa yang diungkapkan oleh Ludwig Josef Johann Wittgenstein bahwa ada tiga hal yang tak bisa dijangkau oleh nalar (logika) manusia: subjek, kematian, dan Tuhan. Meskipun demikian, Muna berarti mencoba untuk meraba atau menerabas kematian yang abstrak. Dia berusaha menghadirkan sebuah kematian sebagai tolok ukur kemanusiaan. Memang sangat bertolak belakang dengan pemikiran Wittgenstein, antara maut dan kemanusiaan: maut tak akan memandang kemanusiaan, tetapi sebaliknya.
Standar normatif yang digunakan oleh Muna untuk memandang kematian dalam konteks lokalitas di Madura, dia menggunakan sudut pandang martabat sebagai pisau bedahnya (hlm. 2). Hal ini juga berbau normatif-relijius. Dalam doktrin agama (Islam), ada beberapa hal yang patut dipertahankan meski mati menjadi taruhannya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga harta dalam konotasinya juga sangat penting, khususnya bagi lingkungan masyarakat Madura dan tak menafikan bagi masyarakat lokal di seluruh pelosok nusantara.
Misalkan, kebiasaan carok yang menjadi pandangan stereotip bagi masyarakat Madura telah tertancap kuat, meski oleh sebagian kalangan berusaha dinetralisir. Keluarga: anak dan istri merupakan harta yang juga wajib dipertahankan sebagaimana doktrin dalam agama Islam. Bahkan, harga diri pun menjadi hal urgen untuk dipertahankan oleh masyarakat Madura, sehingga demi memertahankan hal itu, carok pun dilakukan sebagai ekspresi pertahanan dan ketegasan masyarakat Madura.
Kematian dan Ketentuan Tuhan
Memaknai kematian memiliki cara tersendiri dalam setiap masyarakat di seluruh pelosok negeri. Karya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Muna untuk berekstase menghadapi lingkungan sosialnya yang penuh dengan kekentalan sebuah kultur. Kemungkinan besar, masyarakat di seluruh negeri menjumpai kekentalan sebuah kultur lokalnya yang tak jauh berbeda dengan kultur yang dihadapi Muna. Tetapi itu sulit untuk dihadirkan dengan mudah melalui karya tulis sebagai bentuk introspeksi diri.
Secara tidak langsung, Muna sebenarnya menggugat filsuf sekelas Wittgenstein dengan pernyataannya bahwa tiga hal yang tak dapat dijangkau oleh rasio manusia: subjek, kematian, dan Tuhan. Dalam karya ini, Muna mempertegas bahwa bukan hanya hal itu yang tak dapat dijangkau oleh rasio manusia. Tetapi, jodoh (ketentuan Tuhan) juga sama halnya dengan subjek, kematian, dan Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Wittgenstein (hlm. 20).
Ketentuan Tuhan memiliki makna yang lebih universal. Universalitasnya bisa mengacu pada kematian dan jodoh, yang biasa kita sebut sebagai takdir. Gagasan Wittgenstein tentang kematian sebagai kajian filsafat yang tak bisa dijangkau oleh rasio kiranya sangat tidak tepat. Universalitas maknanya masih kurang memadai. Di sinilah, dari sudut pandang filsafat, Muna secara tidak langsung telah membantah Wittgenstein dalam memandang kematian sebagai bagian dari takdir: ketentuan Tuhan.
Lain halnya lagi ketika dalam tradisi lokal yang dihadapi oleh Muna bahwa kematian bisa dirayakan dengan begitu megah dan mewah dalam konteks masyarakat pedalaman di Madura. Berbeda dengan masyarakat urban yang hidup di perkotaan yang memaknai kematian sangat sederhana. Dalam cerpennya, Pesta Kematian (hlm. 107), dengan tegas Muna mengisahkan tentang kesakralan sebuah kematian agar dirayakan untuk menenangkan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan, sebelum seseorang meninggal, dia telah menyiapkan pesta untuk menyambut kematiannya.
Dalam karya ini, Muna ingin menghadirkan nilai kemanusiaan sebuah tradisi atau budaya dalam lokalitas masyarakatnya sebagai cermin kemanusiaan untuk memaknai segala tradisi yang tentunya tak hanya ada di Madura. Kamuflase yang dilakukan Muna dalam melihat segala tradisi atau budaya masyarakatnya cukup baik dengan menyuguhkan intensitas bahasa yang begitu ritmik, meskipun sebagian kisahnya tergolong absurd di dalamnya. Namun, hal itu ternetralisir oleh paduan kisah yang berkesinambungan pada satu bagian dalam setiap judulnya. Begitu.
Pernah dimuat di Koran Duta Masyarakat, 28 September 2019